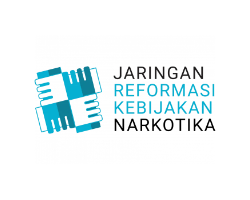War on Drugs: Kebijakan Bias yang Tidak Relevan
Oleh: Nixon Randy Sinaga
Jauh sebelum kebijakan war on drugs mencapai usianya yang ke 50 pada Juni 2021 lalu, banyak laporan yang menyebut dampak struktural yang timbul, mulai pemenjaraan masal hingga brutalisme kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika.[1] Namun sayangnya kebijakan perang narkotika masih menjadi jurus jitu negara dalam penegakan hukum kasus narkotika di Indonesia. Pendekatan punitif tidak berdasar ini justru hanya menjadi “kompetisi adu tangguh” yang tidak menjawab persoalan narkotika di Indonesia.
Promotor pertama kebijakan war on drugs di dunia adalah Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon. Pada 17 Juni 1971, Presiden Nixon mendeklarasikan narkotika sebagai musuh publik nomor satu Amerika. Deklarasi ini membangun paradigma baru pada penegakan hukum tindak pidana narkotika di Amerika. Di sekitar 1970-an populasi penjara Amerika meningkat dari 300.000 hingga 1,6 juta, begitupun jumlah penahanan yang mencapai 100.000.[2] Pendekatan ini tidak memberikan perubahan signifikan dalam penanganan kasus narkotika di Amerika.
Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mengadopsi model kebijakan punitif yang usang ala war on drugs. Pada 4 Februari 2015, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya untuk memerangi narkotika.[3] Pasca deklarasi tersebut, jumlah penghuni lapas terus meningkat. Laporan Kementerian Hukum dan HAM 2019[4] menyebut, lapas pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 148%, kemudian 172% pada 2016, 187% pada 2017, dan 204% pada 2018. Angka-angka ini didominasi oleh tindak pidana narkotika.[5]
Berbagai kampanye digelorakan guna memberi pemaknaan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan paling serius.[6] Konstruksi liar ini telah jelas bertentangan dengan ketentuan dalam General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life (GC/36). Paragraf 35 GC/36 tidak menempatkan delik narkotika sebagai salah satu jenis the most serious crime.[7] Hal ini semakin menegaskan bahwa kebijakan war on drugs telah membangun paradigma yang keliru dan tidak berdasar.
Dampak kebijakan tidak berdasar ini tercermin pada proses penegakan hukum yang bias terhadap pecandu, pengguna, dan/atau penyalahguna narkotika di Indonesia. Glorifikasi perang narkotika justru meningkatkan hasrat tindak kekerasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus narkotika. Kegagalan war on drugs dirasakan negara Filipina setelah Presiden Duterte memerintahkan tembak mati di tempat tersangka penyalahgunaan narkotika. Sayangnya, perintah ini disikapi dengan hasrat emosionalisme aparat kepolisian. Dalam tempo enam bulan Rodrigo Duterte menjabat Presiden Filipina, ia telah membunuh lebih dari 6.100 warganya yang diduga sebagai aktor peredaran narkotika. Orang yang ditangkap seringkali dibunuh tanpa proses peradilan. Kebijakan Duterte terbukti tidak efektif. Peredaran narkoba di Filipina hanya berkurang tidak sampai 10%.[8]
Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Kebijakan war on drugs berdampak pada pelanggaran fair trial yang kerap dinormalisasi oleh aparat penegak hukum tanah air. Berdasarkan hasil pemantauan LBH Masyarakat, sepanjang tahun 2017 terdapat 183 kasus tembak di tempat terhadap terduga pelaku tindak pidana narkotika, dengan total korban sebanyak 215 orang, yakni 99 korban meninggal dunia dan 116 korban luka-luka.[9] Pada tahun berikutnya, terdapat sejumlah 159 kasus tembak di tempat, dengan total korban 199 orang, yakni 68 korban meninggal dunia dan 130 korban luka-luka.[10] Deretan angka ini menegaskan ulang implikasi kebijakan war on drugs yang berdampak pada pelanggaran asas presumption of innocence sebagai bagian dari jaminan fair trial di Indonesia.
Berbeda dengan Indonesia, langkah progresif telah dilakukan Portugal dalam kebijakannya pada penanganan kasus narkotika. Transformasi kebijakan dilakukan melalui dekriminalisasi pengguna narkotika dan mengedepankan intervensi medis sebagai pendekatan penegakan hukum di Portugal. Pada tahun 2001, lebih dari 40% populasi penjara Portugal yang dihukum karena pelanggaran narkoba jauh di atas rata-rata Eropa, dan 70% kejahatan yang dilaporkan terkait dengan narkotika. Pada tahun 2019, proporsi orang yang dihukum karena pelanggaran narkotika di Portugal telah turun secara dramatis menjadi 15,7%.[11] Langkah progresif ini sepatutnya menjadi materi pembanding yang implementatif dalam memformulasi ulang kebijakan narkotika yang humanis pada regulasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Mengatasi permasalahan narkotika harus dilihat secara komprehensif dari hulu ke hilir, tentu dengan memberikan penanganan yang berbeda. Tingginya penggunaan narkotika tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan yang tidak berdasar bukti, fakta, ataupun kajian ilmiah. Pemerintah wajib menghentikan deklarasi dan kebijakan war on drugs serta mengambil langkah legislatif untuk mereformasi kebijakan narkotika melalui pendekatan medis bagi pengguna, pecandu, dan/atau penyalahguna narkotika di Indonesia. Hal serupa juga berlaku bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus narkotika, agar menjamin seluruh prinsip fair trial dalam seluruh proses hukum pada sistem peradilan pidana terpadu.
[1] Benjamin T. Smith, New Documents Reveal the Bloody Origins of America’s Long War on Drugs, https://time.com/6090016/us–war–on–drugs–origins/, diakses pada 22 September 2021.
[2] Jhon F. Pfaff, The War on Drugs and Prison Growth: Limited Importance and Limited Legislative Options, Fordham University School of Law, 2015, p.174.
[3] Carlos Paath dan Priska Sari Pratiwi, Jokowi Promises War on Drugs for a ‘Golden Indonesia’, https://jakartaglobe.id/news/jokowi–promises–war–drugs–golden–indonesia/, diakses pada 23 September 2021.
[4] Divisi Pelayanan Hukum dan HAM , Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kegiatan Pengkajian Hak Manusia di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika, https://jakarta.kemenkumham.go.id/phocadownload/ppid/Laporan%20Pengkajian%20HAM.pdf, diakses pada 22 September 2021.
[5] Akhir tahun 2018 jumlah narapidana kasus narkotika mencapai 115.289 (95% dari total narapidana).
[6] Maria Fatima Bona, Daya Rusak Narkoba Lebih Dahsyat daripada Korupsi dan Terorisme, https://www.beritasatu.com/nasional/541097/daya–rusak–narkoba–lebih–dahsyat–daripada–korupsi–danterorisme, diakses pada 22 September 2021.
[7] General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), on the right of life. Komentar umum ini merupakan interpretasi otoritatif sebagai panduan hasil turunan dari ICCPR. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik),
[8] Ahmad Zaenudin, “War on Drugs”: Gagal di Banyak Tempat, Dirayakan BNN, https://tirto.id/war–on–drugs–gagaldi–banyak–tempat–dirayakan–bnn–gedP, diakses pada 22 Desember 2021.
[9] Ma’ruf Bajammal, Seri Monitor Dan Dokumentasi 2018, Menggugat Tembak Mati Narkotika, LBH Masyarakat, Jakarta, 2018, hlm.7.
[10] Ma’ruf Bajammal, Seri Monitor Dan Dokumentasi 2019, Tembak Mati di Tempat: Membunuh Negara Hukum Indonesia, LBH Masyarakat, Jakarta, 2019, hlm.9.
[11] Harvey Slade, Case Study: Drug Decriminalisation in Portugal: Setting the Record Straight, https://transformdrugs.org/blog/drug–decriminalisation–in–portugal–setting–the–record–straight, diakses pada 24 September 2021.