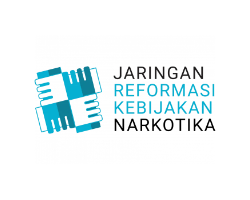Kasus Kekerasan Seksual oleh Anggota Polda Sulsel Harus Diproses dengan UU TPKS, Hal ini juga Bukti konkret revisi KUHAP dan UU Narkotika harus segera dilakukan
Baru-baru ini, kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan terjadi. Pada 7 Desember 2023, Anggota Polisi Briptu Sanjaya terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang merupakan tahanan narkotika perempuan di Rutan Polda Sulawesi Selatan. Dalam proses sidang etik yang digelar, terungkap bahwa pelaku telah berulang kali melakukan kekerasan seksual kepada korban. Namun atas perbuatannya, pelaku hanya dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama 7 tahun. Sebelumnya korban telah melaporkan peristiwa ini secara pidana di SPKT Polda Sulsel pada 22 Agustus 2023, namun oleh Kepolisian belum juga menetapkan pelaku sebagai tersangka dan melakukan penyidikan serius.
Setiap tahunnya kita pasti mendengar praktik penyiksaan dan kekerasan dilakukan oleh kepolisian. Dalam kurun waktu Juni 2022-Mei 2023, KontraS menemukan setidaknya terdapat 54 peristiwa penyiksaan, penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat di Indonesia. Angka tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya jumlah kasus riil yang lebih banyak. Dalam berbagai peristiwa tersebut, Kepolisian menjadi aktor yang dominan melakukan tindak penyiksaan dengan 34 peristiwa.
Lebih lanjut, dalam laporan KontraS menemukan dari 54 peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi 31 peristiwa diantaranya tidak ada proses penindakan terhadap pelaku penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Hal ini menunjukkan belum adanya komitmen penuh oleh lembaga negara untuk dapat menindak tegas pelaku penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi melalui mekanisme yang ada.
Dalam institusi Polri sendiri, KontraS mencatat bahwa setidaknya terdapat 19 kasus yang tidak ada proses penindakan terhadap pelaku penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh Polisi. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak berubah menjadi lebih baik, minimnya tindak lanjut atas peristiwa penyiksaan dan kekerasan yang membuat kasus berulang terjadi dari tahun ke tahun dengan pola yang sama. Data ini menggambarkan bagaimana kultur kekerasan dan impunitas yang langgeng dalam suatu institusi negara.
Selain penyiksaan, kekerasan seksual saat menjalani proses hukum juga kerap terjadi dalam tahap penahanan, terlebih dalam perkara narkotika. Penyiksaan dalam proses hukum ini sesungguhnya telah lama dilaporkan komunitas pengguna narkotika di seluruh Indonesia. Dimana perempuan pengguna narkotika sangat rentan dengan kekerasan berbasis gender, apalagi di negara yang mengutamakan pendekatan penghukuman bagi pengguna narkotika. Dalam laporan kajian perempuan di lingkar napza (PKNI:2016) ditemukan sebagian besar perempuan dalam lingkaran narkotika mengalami riwayat kekerasan oleh polisi dalam tahap penangkapan dan penahanan. Dimana 60% dari perempuan yang pernah kontak dengan polisi mengalami pelecehan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.
Praktik-praktik penyiksaan dan kekerasan pada tahanan di kepolisian ini disebabkan oleh:
Pertama, berkaitan dengan hukum acara pidana di Indonesia. Saat ini ada cacat mendasar dalam KUHAP, bahwa keputusan untuk menangkap dan menahan ada di tangan penyidik sendiri tanpa berimbang. Jika melihat ketentuan ICCPR dan Komentar Umum mengenai hak kemerdekaan, keputusan menahan dalam peradilan pidana harus datang dari otoritas lain untuk menjamin pengawasan berjenjang, misalnya dengan pelibatan hakim pemeriksa pendahuluan. Pun saat ini, penilaian kebutuhan penahanan harus substansial, tidak hanya berbasis ancaman pidana.
Mau tak mau KUHAP harus direvisi, kewenangan penahanan di kantor-kantor kepolisian juga harus dihapuskan.
Kedua, kebijakan keras narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mudah sekali menjerat pidana seseorang. Terbukti kasus paling banyak datang dari implementasi kebijakan narkotika, banyak korban penyiksaan datang dari kasus penggunaan narkotika yang sedari awal tidak perlu diproses secara pidana, harusnya dapat diintervensi dengan pendekatan kesehatan. Revisi UU Narkotika yang menjamin dekriminalisasi bagi penggunaan narkotika harus didorong.
Ketiga, minimnya pengawasan yang efektif pada tempat-tempat penahanan secara real time. Penahanan pada tersangka/terdakwa adalah situasi yang timpang, dimana tersangka/terdakwa berhadap langsung dengan kewenangan negara di ruang tertutup. Sehingga dalam proses ini harus ada pengawasan yang ekstra dan berlapis, baik internal maupun eksternal.
Atas hal ini, ICJR mendesak bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polisi Briptu Sanjaya merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang harus diproses dengan hukum acara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putusan sidang etik yang telah dilaksanakan hanya akan menjadi preseden buruk kepolisian dalam memandang kekerasan seksual sebagai hal yang lumrah dilakukan.
Selain itu, UU TPKS yang memberikan jaminan hak-hak korban yang komprehensif termasuk penanganan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan oleh pelaku kekerasan, dan pemulihan korban harus dilaksanakan.
Lebih lanjut, dalam tataran normatif yang lebih besar, Pemerintah dan DPR segera melakukan langkah konkret melakukan revisi KUHAP dan UU Narkotika. Penahanan di kantor kepolisian harus dilarang dalam KUHAP ke depan, dekriminalisasi pengguna narkotika harus disusun dalam revisi UU Narkotika.