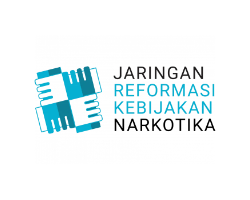Meneroka Politik Moralitas dalam Kebijakan Narkotika
Oleh: Miko Ginting, Pengajar Hukum Pidana di STH Indonesia Jentera
Fenomena kepadatan penghuni di institusi pemasyarakatan adalah buah dari kegagalan kebijakan narkotika. Sebuah pernyataan yang sebenarnya ganjil, karena sekalipun diakui sebagai sebuah “kebenaran”[1], tetapi ia bersifat kekal dan berulang. Maka, keanehan ini menuntun kita pada satu pertanyaan: mengapa jalan keluar tak kunjung teretas?
Tentu, jalan keluar di sini harus diartikan sebagai sebuah reformasi (pembentukan ulang) kebijakan politik negara terkait narkotika. Dengan demikian, selisik tidak bisa tidak perlu diarahkan kepada para perumus kebijakan dan asumsi-asumsi yang diciptakan para pengupaya perubahan kebijakan terhadapnya. Asumsi bahwa perumus kebijakan adalah “agensi yang rasional”, dalam pengertian punya keinsyafan untuk mencapai keuntungan yang optimal dan menghindari kerugian yang sebenar-benarnya, tampaknya perlu ditinjau ulang.
Dari deskripsi yang tentu menyederhanakan, misalnya, bentuk politik kebijakan negara (P)[2] berbanding lurus dengan biaya yang timbul (C)[3], baik biaya finansial (Cf)[4], biaya sosial (Cs)[5] maupun biaya lain yang tidak terperkirakan (Cu)[6]. Ketika asumsi bentuk politik kebijakan negara berupa mekanisme pidana (Pp)[7] terhadap pengguna narkotika adalah sebuah disinsentif, maka yang terjadi adalah dengan semakin banyaknya penggunaan mekanisme pidana, semakin banyak pula biaya yang timbul (P (Pp)= C (Cf + Cs + Cu). Sebaliknya, dengan semakin sedikit kebijakan pidana yang diterapkan, maka semakin sedikit pula biaya yang harus ditanggung.
Pengupaya perubahan kebijakan, terutama mereka yang mendorong pilihan-pilihan yang lebih rasional, tentu sulit mendapati situasi yang anomali ini. Di satu sisi, terdapat asumsi untuk menempatkan perumus kebijakan sebagai “agensi yang rasional”. Namun, di sisi lain, pada akhirnya mendapati bahwa sandaran “pilihan-pilihan berbasis rasionalitas”[8] ternyata tidak cukup untuk memberikan jawaban. Kembali kepada pernyataan di awal, permasalahannya tetap kekal dan berulang sementara perubahan kebijakannya tidak kunjung dilakukan.
Moralitas politik
Optik perlu diarahkan kepada aspek lain yang fundamental, yaitu posisi kultur dalam suatu perubahan hukum (legal change). Kultur yang dimaksud di sini adalah dalam pengertian sosiologis, yaitu sebagai sebuah makna yang saling dipertukarkan (shared meanings) dalam suatu komunitas atau masyarakat.[9] Dengan demikian, sebuah perubahan hukum tidak hanya terjadi dalam formalitas konfigurasi kekuasaan, tetapi lebih banyak dikontribusikan oleh sekelompok perbedaan akan nilai (values) dan sikap (attitudes) dalam suatu masyarakat.[10]
Perspektif ini sangat relevan, terutama apabila dikontekskan pada suatu masyarakat yang majemuk dan berciri bertukar nilai dan kepercayaan (shared of values and beliefs)[11], seperti Indonesia. Dari sini, kita bisa melacak bahwa sikap untuk mempertahankan kebijakan status quo terkait narkotika adalah lebih berdasarkan nilai dan kepercayaan yang berbeda, baik di dan di antara perumus kebijakan maupun bagaimana mereka mengolah aspirasi yang muncul dari masyarakat.
Penerjemahaan nilai dan kepercayaan yang majemuk kepada suatu kebijakan publik ini disebut dengan politik moralitas.[12] Konsep ini memberikan perhatian pada proses di mana perumus kebijakan dalam menentukan apa yang “benar” dan apa yang “salah” berbasis pada seperangkat nilai dan kepercayaan mendasar kemudian memberikan legitimasi terhadapnya melalui suatu mekanisme hukum.[13] Dengan demikian, politik moralitas menyasar kepada apa yang secara moral “diterima” atau “tidak diterima” dalam suatu kebijakan publik, salah satunya melalui mekanisme pemidanaan.[14]
Kebijakan terkait penggunaan narkotika tidak lain merupakan arena pertarungan politik moralitas. Untuk menelisiknya lebih jelas, kita perlu membedakan mana pandangan yang termanifestasikan dan mana pandangan yang laten. Dalam pandangan yang termanifestasikan, dapat diduga bahwa arus yang dominan menginginkan kebijakan publik berupa rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dan pengurangan terhadap penggunaan mekanisme pidana. Namun, sekalipun demikian, dalam pandangan yang laten, bukan berarti terhadap pengguna narkotika tidak dikenakan mekanisme apapun.
Dalam berbagai kasus, politik moralitas yang bersifat laten bekerja dengan memposisikan pengguna narkotika dipandang sebagai “orang yang tidak bermoral atau orang yang berdosa”.[15] Oleh karena itu, meskipun tidak selalu dalam bentuk pemenjaraan, respons “negara” didorong untuk harus tetap bekerja, misalnya dalam bentuk penyuluhan agama.[16] Dugaan lain, bentuk rehabilitasi yang bersifat wajib dalam UU Narkotika, salah satunya adalah berangkat dari pandangan moralitas ini. Bahwa perlu dilakukan “penyembuhan” medis dan mental (rohani) terhadap pengguna narkotika.
Pandangan moralitas politik yang laten ini adalah konsiderasi utama dalam reformasi tata kelola penggunaan narkotika. Dorongan dari komunitas yang mewakili pandangan tertentu dan “nilai internal” bahwa sungguh “tidak bermoral” apabila penggunaan narkotika tidak direspons oleh negara menjadi pertimbangan dominan dalam perubahan kebijakan narkotika. Oleh karena itu, tidak terlalu mengherankan bahwa sikap bertolak belakang dengan sains acapkali muncul dalam diskursus mengenai reformasi kebijakan penggunaan narkotika.
Narasi baru
Pada akhirnya, kebijakan baru mengenai penggunaan narkotika tidak lagi sekadar berhadapan dengan kebijakan yang “ideal atau tepat”. Dalam arti, tidak lagi sekadar berhadapan dengan apakah kriminalisasi terhadap penggunaan narkotika atau rehabilitasi bersifat wajib adalah tepat atau tidak. Namun, lebih kepada bagaimana mengelola sentimen moralitas dari perumus kebijakan dan kelompok masyarakat, terutama yang sifatnya laten.
Narasi baru sangat diperlukan muncul dari pengupaya perubahan kebijakan. Di titik ini, pekerjaan menjadi jauh lebih rumit, yaitu mendorong “normalisasi” penggunaan narkotika sementara yang dihadapi adalah suatu sentimen yang tertutup dan berbasis moralitas.
[1] Paling tidak, pernyataan ini dikonfirmasi oleh semua pihak, baik dari sisi pemerintah, DPR, maupun masyarakat. Lihat pernyataan yang cukup tajam dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, di sini https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908205134-12-691689/yasonna-tuding-uu-narkotika-biang-kerok-lapas-over-kapasitas. Begitu pula pernyataan salah satu anggota DPR, Arsul Sani, di sini https://www.voaindonesia.com/a/anggota-dpr-ingatkan-pemerintah-soal-revisi-uu-narkotika-/6235733.html. Termasuk penyataan dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil di sini https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912143503-12-693169/lsm-pemerintah-tak-becus-revisi-uu-narkoba-lapas-jadi-sesak.
[2] P di sini berarti policy (kebijakan).
[3] C adalah cost (biaya).
[4] Cf adalah financial cost (biaya finansial/moneter).
[5] Cs adalah social cost (biaya sosial, termasuk tetapi tidak terbatas, misalnya, biaya yang ditanggung masyarakat, pengguna dan keluarganya, dan sebagainya).
[6] Cu adalah unintended cost (biaya yang tak tidak diperkirakan).
[7] Pp adalah criminal policy (kebijakan pemidanaan).
[8] Salah satu yang bisa dirujuk adalah Richard A. Posner, 1997. Rational Choice, Behavioral Economics, and the Law. 50 Stanford Law Review, hlm 1551-1575.
[9] Pengertian ini dikemukakan salah satunya oleh Stuart Hall, 1997. Representation: Cultural Representation and Signifying Practices. Glasgow: The Open University.
[10] Lawrence M. Friedman, 2001. Some Comments on Cotterrel and Legal Transplant, dalam David Nelken dan Johannes Fest (ed), 2001. Adapting Legal Cultures. Oñati International Series in Law and Society. Oxford: Hart Publishing, hlm. 93-99.
[11] Dengan “meminjam” empat tipologi social action dari Max Weber, Roger Cotterrel mengemukakan relasi tipologi masyarakat dengan perubahan hukum. Lihat Roger Cotterrel, 2001. Is There a Logic of Legal Transplant? Dalam David Nelken dan Johannes Fest (ed), ibid.
[12] Salah satu contoh kasus yang diberikan oleh Meier adalah pengaturan mengenai narkotika di Amerika Serikat. Lihat Kenneth J. Meier, 1999. Drugs, Sex Rock and Roll: A Theory of Morality Politics. Policy Studies Journal, Vol. 27, No. 4, hlm. 681-695.
[13] Chistopher Z. Mooney, 1999. The Politics of Morality Policy. Policy Studies Journal, Vol. 27, No. 4, hlm 675-680.
[14] Ronald Weitzner, 2009. Legalizing Prostitution: Morality Politics in Western Australia. British Journal of Criminology, Vol. 49, No.1, hlm 88-105.
[15] Salah satu contoh, pada 2017, Badan Narkotika Nasional dan Majelis Ulama Indonesia menerbitkan sebuah buku berjudul “Pandangan Islam tentang Bahaya Penggunaan Narkoba”. Lihat https://news.detik.com/berita/d-4840516/medina-zein-positif-narkoba-ini-dalil-haram-menggunakan-narkotika-dalam-islam
[16] Salah satu organ negara yang utama menyelenggarakan kegiatan semacam ini adalah Badan Narkotika Nasional. Lihat https://bnn.go.id/penanggulangan-narkoba-tingkatkan-peran-tokoh-dan-penyuluh-agama/ dan https://bnn.go.id/penguatan-peran-penyuluh-agama-dan-kua-dalam-p4gn/