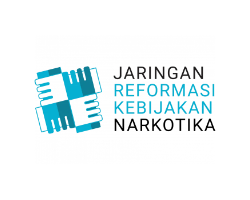Peluang Diversi pada Pengguna Narkotika pada untuk Mengurangi Angka Overcrowding di Indonesia
oleh: Dio Ashar Wicaksana
Indonesia Judicial Research Society
Situasi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kembali menuai perdebatan akan situasi kapasitas Lapas semenjak terjadinya kebakaran di Lapas Kelas I Tanggerang pada 8 September 2021 lalu. Kejadian tersebut bukanlah suatu kejadian baru di Indonesia, dimana berdasarkan catatan dari ICJR, IJRS dan LeIP (2021) setidaknya terdapat 13 (tiga belas) Lapas yang terbakar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini. Dimana terdapat 10 (sepuluh) Lapas yang terbakar dalam kondisi kelebihan penghuni (overcrowding).[1] Bahkan jika melihat angka overcrowding pada Lapas Kelas I Tangerang sendiri sudah mencapai angka 245%, dan saat ini dihuni oleh 2069 orang.[2]
Secara nasional, angka overcrowding Lapas di Indonesia juga masih menyimpan permasalahan secara menyeluruh. kapasitas penjara Indonesia saat ini sudah tidak cukup untuk menampung para narapidana. Per-Juli 2020, beban rumah tahanan (rutan)/lembaga permasyarakatan (lapas) sudah mencapai angka 176% dari kapasitas yang dapat disediakan untuk 133.086 orang[3]. Tingginya angka tersebut juga disebabkan banyaknya kelompok pengguna narkotika yang dipenjara, hingga total jumlah pengguna narkotika di dalam rutan/lapas mencapai 40.470 orang per-Juli 2020.[4] Tentunya kondisi overcrowding ini perlu menjadi perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Mengingat dengan kondisi tidak ideal tersebut, dapat berimplikasi pada kurang maksimalnya pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan.
Akar masalah penyebab situasi overcrowding Lapas ini berakar dari aspek pemidanaan Indonesia yang menempatkan penjara sebagai solusi utama penyelesaian suatu permasalahan. Menurut keterangan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Eddy O.S Hiarief (2021), menyebutkan bahwa persoalan utama dari situasi overcrowding di Indonesia adalah terkait aspek substansi hukum, dimana kerja lembaga peradilan yang kerap memenjarakan seseorang.[5] Salah satu regulasi yang menjadi permasalahan adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan minimnya mekanisme penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan dalam legislasi Indonesia.
Padahal saat ini, kebijakan narkotika dan pemidanaan sudah mulai bergeser dari pendekatan kriminalisasi menjadi penerapan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Melihat adanya kebutuhan pendekatan HAM dalam kebijakan narkotika, komunitas global mulai mencoba mengubah pendekatan kebijakan narkotika dengan memberi jalan alternatif bagi perang atas narkotika. Beberapa pendekatan mulai mencoba memperhatikan adanya alternatif pendekatan kesehatan serta adanya pendekatan dekriminalisasi, depenelisasi dan regulasi. Pendekatan tersebut dinilai bisa berdampak positif, seperti contohnya pendekatan dekriminalisasi nantinya harus disertai adanya komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran hak sipil dan politik terhadap pengguna narkotika.[6]
Selain itu, ketiga pendekatan tersebut juga dinilai bisa menjadi jawaban atas respon dari kegagalan pendekatan war on drugs, dimana pendekatan tersebut dapat membuka peluang adanya pelanggaran HAM terhadap penegakan hukum narkotika di beberapa negara, seperti peluang adanya kekerasan dari aparat penegak hukum, kriminalisasi terhadap pengguna narkotika serta mengurangi akses kesehatan dan melakukan pemaksaan pemeriksaan Kesehatan tanpa adanya persetujuan dari pihak terkait.[7]
Melihat dengan kebutuhan tersebut, sudah seharusnya pemerintah Indonesia mulai mencoba memikirkan alternatif pendekatan kebijakan narkotika dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika kedepannya. Apalagi RUU Narkotika juga menjadi salah satu daftar RUU yang menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Indonesia tahun 2020-2024[8]. Salah satu alternatif kebijakan yang dapat diterapkan adalah mekanisme diversi, yaitu konsep diversi sendiri mengacu pada langkah-langkah untuk memberikan suatu alternatif mekanisme selain mekanisme penjatuhan sanksi atau penahanan terhadap orang yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika, termasuk para pengguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan diversi itu sendiri dapat diterapkan melalui program, kebijakan ataupun praktik yang menggunakan intervensi sosial dan kesehatan serta pengurangan dampak buruk dari penanganan narkotika. Sehingga konsep ini tidak mengedepankan lagi pendekatan yang mengutamakan penangkapan, penahanan serta pemenjaraan terhadap pengguna narkotika. Penerapan diversi ini dapat diterapkan pada seluruh proses peradilan pidana, sejak penyidikan higga pelaksanaan putusan hakim, dimana langkah-langkah tersebut dapat diterapkan pada juridiksi-juridiksi yang telah menerapkan dekriminalisasi baik secara de jure ataupun de facto.[9]
Oleh karena itu, penulis mencoba mengenalkan secara dasar mengenai mekanisme diversi dan bagaimana peluang penggunaan mekanisme diversi dapat diterapkan pada pembahasan RUU Narkotika kedepannya. Agar kebijakan pidana narkotika Indonesia kedepannya bisa berkontribusi terhadap mengurangi dampak buruk overcrowding Lapas dan pemenuhan hak kesehatan bagi pengguna narkotika.
Catatan Implementasi Kebijakan Narkotika di Indonesia
Tingginya angka pengguna narkotika di rutan/lapas juga disebabkan tidak jelasnya pelaksanaan dari pasal 111, 112, dan 117 UU Narkotika dengan ketentuan pasal 127 UU Narkotika. Di dalam Pasal 127 Undang-Undang (UU) Narkotika menyebutkan bahwa Hakim dapat memberikan program rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika setelah persidangan. Namun, pengaturan di dalam undang-undang masih menyisakan beberapa permasalahan. Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI) menyebutkan bahwa ada beberapa permasalahan dalam kebijakan narkotika dalam UU Narkotika, Pertama kebijakan narkotika tidak memisahkan antara pengguna dan pelaku perdagangan gelap narkotika. UU Narkotika memberikan celah bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk merekayasan dan memeras pengguna narkotika. Ketiga, UU Narkotika tidak memandang secara jelas bahwa pengguna adalah korban permasalahan perdagangan gelap narkotika. Keempat, rehabilitasi diartikan sebagai pengobatan dan bukan sebagai pemulihan. Kelima, kebijakan narkotika saat ini tidak mengakomodir konsep pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika.[10]
Dalam implementasi kebijakan narkotika masih banyak aparat penegak hukum yang meyakini bahwa mengirimkan pengguna narkotika kedalam penjara merupakan praktik yang umum. Di dalam riset yang belum terpublikasikan dari MaPPI-FHUI (2015) menunjukkan bahwa hanya 6 kasus dari 21 kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan wilayah Jakarta pada tahun 2015 yang menyertakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotik. Tantangan lainnya adalah tidak konsistennya hukum di Indonesia. Meskipun terdapat pasal yang menyertakan rehabilitasi, akan tetapi terdapat pasal lainnya yang mendorong adanya penerapan penjara. Pasal 112 UU Narkotika menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika akan mendapatkan hukuman penjara. Definisi tersebut tentunya akan menidentikasi pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan, karena secara logika sesorang yang menggunakan narkotika pastinya akan memilki dan menyimpan narkotika. Riset dari Institute for Criminal Justice Reform (2012) menunjukan hanya 10% putusan Hakim Agung yang memberikan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika[11]. Aparat penegak hukum ada kecendrungan lebih memilih menggunakan ketentuan di dalam Pasal 127 dibandingkan pasal 112 pada kasus narkotika karena semata-mata lebih mudah untuk dibuktikan.[12]
Ironisnya dengan pendekatan seperti ini, penyalahguna, terutama yang baru sesekali menggunakan atau rekreasional, bisa berujung diselesaikan dengan pemenjaraan. Padahal memenjarakan pengguna narkotika dapat memperburuk keadaan terhadap mereka karena merajalelanya praktik korupsi di dalam penjara[13]. Narapidana bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan dengan harga, termasuk narkotika. Gabriel J. Culbert (2014) mengungkapkan bahwa 56% narapidana masih menggunakan narkotika di penjara wilayah Jakarta.[14] Para responden juga mengakui bahwa mereka masih mendapatkan akses terhadap narkotik illegal semalam masa mereka di dalam penjara[15]. Bahkan menurut keterangan dari Badan Narkotika Nasional (2017), menyatakan bahwa 50% dari peredaran gelap narkotika terjadi di dalam penjara[16].
Selain ketentuan dalam UU Narkotika, 7 (tujuh) institusi secara bersama mengeluarkan kebijakan yang sifatnya lebih teknis dan koordinatif, yaitu Peraturan Bersama 7 institusi[17] tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi diterbitkan pada 2014. Peraturan ini berusaha memberikan kejelasan pedoman untuk memberikan jaminan rehabilitasi pada pecandu dan korban penyalahguna narkotika, baik dalam sistem peradilan pidana maupun dalam lembaga rehabilitasi setelah ataupun diluar sistem peradilan pidana lewat proses assesement oleh Tim Assessent Terpadu (TAT). Namun sayangnya, kendati jaminan rehabilitasi sudah diatur lebih jelas, namun rehabilitasi masih belum jadi pilihan utama, Penelitian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Rumah Cemara dan EJA pada 2015 di PN Surabaya menemukan hanya 6% putusan hakim yang menempatkan pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi[18].
Mekanisme Diversi Pada Pengguna Narkotika
Secara kebijakan, sebenarnya Indonesia sudah membuka adanya peluang diversi melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti contohnya tersedianya mekanisme rehabilitasi di dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun pada akhirnya, pemerintah Indonesia kembali melakukan revisi terhadap UU Narkotika melalui dibentuknya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan ketentuan undang-undang ini mencoba menyeimbangkan penggunaan pendekatan hukum pidana dengan pendekatan kesehatan kepada pengguna narkotika. Ketentuan tersebut bisa dilihat dimana dalam Pasal 4 (d) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan salah satu tujuan adanya UU tentang Narkotika ini adalah menjamin adanya pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pencandu narkotika.
Akan tetapi, kebijakan narkotika dalam ketentuan UU Narkotika ini masih mengedepankan pendekatan hukum pidana dibandingkan pendekatan kesehatan. Hal ini bisa terlihat dari beberapa ketentuan pasal dalam undang-undang ini masih menggunakan perspektif hukuman sebagai alat untuk penyelesaian permasalahan narkotika di Indonesia. Seperti contoh pada Pasal 134 UU Narkotika memberikan ancaman hukuman pidana bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan sengaja tidak melaporkan diri. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang berkembang di beberapa negara – yang mengedepankan pendekatan kesehatan bagi para pencandu atau pengguna narkotika.
Ketentuan rehabilitasi yang ada di dalam UU Narkotika juga dinilai lebih cendrung memposisikan dalam pendekatan hukuman dibandingkan dengan pendekatan kesehatan. Pandangan ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 54 UU Narkotika, dimana mewajibkan para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga dengan adanya kata “wajib” menempatkan kosekuensi pengenaan sanksi tertentu apabila tidak dilakukan.[19]
Selain itu, pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan ketentuan UU Narkotika juga menimbulkan beberapa permasalahan lainnya. Hal tersebut terjadi karena tidak jelasnya definisi antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di UU Narkotika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 memang membedakan pengertian antara ketiga definisi tersebut, seperti penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa haka tau melawan hukum[20]. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika[21]. Sementara pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis[22].
Pemisahan definisi tersebut pada awalnya diharapkan agar berakibat pada penanganan atau tindakan berbeda yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika. Seperti contohnya, penyalahguna narkotika yang bisa mendapatkan hak rehabilitasi berdasarkan proses peradilan adalah korban penyalahguna[23] serta pecandu narkotika.[24] Sehingga dengan pemisahan definisi tersebut menandakan bahwa penyalahguna narkotika akan diancam dengan sanksi penjara, kecuali penyalahguna narkotika tersebut merupakan korban penyalaguna narkotika.
Rumusan tersebut menyebabkan penyalahguna narkotika, yang bukan merupakan pecandu dan korban penyalahgunaan kesulitan untuk memperoleh penanganan rehabilitasi. Hal tersebut berdampak tingginya pengguna narkotika di penjara, sehingga menyebabkan kapasitas penjara menjadi overcrowding, hal ini disebabkan karena jumlah penghuni penjara yang berasal dari kejahatan narkotika meningkat sangat pesat.[25]
Selain itu, kebijakan rehabilitasi pada UU Narkotika yang mewajibkan setiap pengguna untuk rehabilitasi bisa menjadi kurang tepat. Karena perlu ditelusuri lebih jauh, apakah semua pengguna narkotika memang memerlukan adanya intervensi medis sebagai suatu solusi. Sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan mencoba menjelaskan kategori pengguna narkotika untuk memahami lebih jauh ragam kondisi dan kebutuhan dari para pengguna narkotika. Hal ini menjadi penting karena setiap orang dengan penggunaan zat, baik pecandu, penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika memiliki karakteristik, masalah dan kebutuhan yang berbeda-beda. Mengacu dari United Nations Office Drugs and Crime (UNODC), terdapat 6 (enam) sub-populasi dari populasi yang menggunakan narkotika, yaitu:[26]
- Pengguna narkotika yang tidak mengalami ketergantungan, banyak pengguna dalam kelompok ini menggunakan untuk rekreasional dan tidak berpikir hal tersebut merupakan suatu masalah, apalagi berpikir untuk mencari pertolongan. Namun demikian perilaku mereka beresiko untuk penggunaan zat yang lebih serius, sehingga diperlukan adanya layanan intervensi dan deteksi dini
- Pengguna narkotika dengan cara suntik, secara umum memiliki pola penggunaan ketergantungan dan beresiko tertular HIV dan/atau hepatitis. Sehingga secara umum diperlukan layanan untuk mengurangi kosekuensi buruk pada kesehatannya dan memerlukan layanan terapi dan rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
- Pecandu, umumnya membutuhkan layanan terapi dan rehabilitasi yang spesifik, bersifat intensif dan/atau residensial, serta disediakan adanya layanan paska rehabilitasi seperti layanan perumahan, pekerjaan dan pelatihan keterampilan
- Pengguna narkotika yang terintoksikasi secara akut, memiliki resiko penyakit dan kematian yang tinggi terkait dengan pola penggunaannya yang bersifat impulsive, atau berkaitan dengan efek samping zat yang digunakan atau overdosis zat. Kondisi ini tidak selalu terkait dengan kondisi ketergantungannya, sehingga bisa saja orang yang tidak memiliki ketergantungan tinggi tapi memiliki potensi bahaya akibat pola penggunaannya. Sehingga dibutuhkan layanan intoksikasi akut pada unit gawat darurat, dimana layanan ini tidak selalu tersedia pada layanan terapi dan rehabilitasi
- Pengguna narkotika dalam kondisi gejala putus zat, dampak dari penghentian penggunaan zat menyebabkan kelompok ini mengalami suatu tanda dan gejala seperti rasa nyeri, gangguan tidur, dan rasa cemas. Kelompok ini membutuhkan perhatian medis dan manajemen putus zat yang terencana, baik melalui rawat jalan maupun perawatan residensial, disesuaikan dengan kebutuhannya
- Pengguna narkotika dalam masa pemulihan, umumnya kelompok ini sudah melewati tahap rehabilitasi dan terapi. Sehingga dibutuhkan adanya layanan yang dapat membantu mempertahankan pemulihannya, seperti pelatihan vokasional, program paska rehabilitasi, program bantu diri, dan sebagainya.
Melihat dari karakteristik sub-populasi tersebut, ada sub-populasi pengguna narkotika yang tidak mengalami ketergantungan. Sub-populasi ini bisa jadi tidak membutuhkan intervensi medis yang terlalu jauh. Sehingga diperlukan suatu mekanisme diversi lainnya, yang tidak hanya mewajibkan rehabilitasi, yang bisa menjadi lebih efektif sebagai langkah preventif bagi pengguna dalam sub-populasi ini tidak mengalami dampak yang lebih serius kedepannya.
Sebenarnya, alternatif mekanisme ini bisa dengan menggunakan mekanisme percobaan/bersyarat. Mekanisme percobaan sendiri mengacu pada ketentuan Pasal 14a KUHP terkait pidana bersyarat, dimana merupakan suatu praktik hukum, Ketika hakim dalam menjatuhkan suatu putusan memberikan syarat-syarat tertentu, sehingga orang yang dipidanakan tidak perlu menjalankan hukuman pidana selama masa percobaan.
Mekanisme pidana percobaan tersebut sebenarnya sudah diperkenalkan di Indonesia melalui Pedoman Penuntutan No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika – dimana mekanisme pidana percoabaan dapat diberikan kepada pengguna narkotika yang tidak mengalami ketergantungan. Akan tetapi, sayangnya Kejaksaan dalam mekanisme ini hanya baru menerapkan syarat percobaannya adalah mekanisme rehabilitasi, padahal mekanisme pidana percobaan sebenarnya bisa diikuti tindakan-tindakan lain, seperti kerja mekanisme wajib lapor atau mekanisme pengawasan dari pemerintah.
Mekanisme diversi yang perlu disediakan adalah mekanisme intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pengklasifikasian pengguna narkotika sesuai sub-populasi yang dijelaskan sebelumnya. Intervensi kesehatan dapat dilakukan terhadap pengguna narkotika yang membutuhkan pertolongan medis. Akan tetapi, pengguna narkotika yang tidak mengalami ketergantungan perlu dibedakan agar dapat dikenakan mekanisme selain rehabilitasi, seperti mekanisme percobaan yang ada dalam mekanisme pemidanaan percobaan.
Namun dalam merumuskan kebijakan RUU Narkotika kedepannya, terdapat 2 (dua) prinsip yang perlu menjadi perhatian khusus, yaitu (1) prinsip sukarela dan partisipatif, serta (2) dapat dilepaskannya mekanisme peradilan pidana bagi para pengguna narkotika berdasarkan hasil asesmen. Sehingga pemberikan mekanisme rehabilitasi ataupun percobaan dapat diterapkan sejak awal proses dan tidak perlu dilimpahkan kepada proses peradilan pidana, apabila memang kondisi pengguna tersebut bukanlah termasuk kategori pengedar narkotika. Sehingga bentuk pertanggung jawaban perbuatannya tidak perlu dibebankan pada proses peradilan pidana. Tim asesmen sendiri dapat dibentuk dengan terdiri dari unsur dokter dan Psikolog yang melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.
[1] ICJR, IJRS dan LeIP (Rilis Pers) Kebakaran (Lagi) di Lembaga Permasyarakatan: Evaluasi dan Investigasi Harus Segera Dilakukan diakses pada http://ijrs.or.id/rilis-pers-kebakaran-lagi-di-lembaga-pemasyarakatan-evaluasi-dan-investigasi-harus-segera-dilakukan/ tanggal 22 September 2021
[2] Ibid
[3] ICJR, IJRS dan LeIP, (Rilis Pers) Kondisi Kasus Covid-19 di Rutan/Lapas Harus Mendapatkan Perhatian, Overcrowding Harus Diselesaikan Bersama diakses pada http://ijrs.or.id/rilis-pers-kondisi-kasus-covid-19-di-rutan-lapas-harus-mendapatkan-perhatian-overcrowding-harus-diselesaikan-bersama/ tanggal 22 September 2021
[4] Ibid
[5] Eddy O.S Hiarief sebagaimana dikutip pada https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6149a3307191f/solusi-persoalan-overcrowding-lapas-butuh-perubahan-sistem-pemidanaan tanggal 22 September 2021
[6] Ibid, 6-7
[7] Ibid, Hal. 4
[8] Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Program Legislasi Nasional pada https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list diakses tanggal 22 September 2021
[9] Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Naskah Akademik RUU Narkotika (Draft 1), (Depok: MaPPI-FHUI, 2018), Hal. 53
[10] Totok Yulianto sebagaimana dikutip dalam https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/06/24/o9a3j6361-ini-5-permasalahan-kebijakan-narkotika-di-indonesia pada tanggal 22 September 2021
[11] Erasmus A.T. Napitupulu dan Miko S. Ginting, Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika, (Jakarta: ICJR dan LeIP, 2013) diakses pada http://icjr.or.id/potret-situasi-implementasi-kebijakankriminal-terhadap-pengguna-narkotika/ tanggal 29 Desember 2020
[12] ICJR sebagaimana dikutip di dalam https://tirto.id/dilema-hukuman-rehabilitasi-narkoba-cvF8 diakses pada tanggal 22 September 2021
[13] Drugs, Corruption Rampant in Indonesian Prisons diakses pada https://www.voanews.com/east-asia/drugs-corruption-rampant-indonesian-prisons tanggal 22 September 2021
[14] Gabriel J. Culbert, et all, Within-Prison Drug Injection among HIV-Infected Male Prisoners in Indonesia: A Highly Constrained Choice, Drug and Alcohol Dependence Vol. 149 (2015), Hal.71
[15] Ibid, Hal. 76
[16] BNN: 50% Peredaran Narkoba Dikendalikan dari Penjara diakses pada https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713145408-12-227647/bnn-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-penjara tanggal 28 Desember 2020
[17] Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik
[18] Berdasarkan Penelitian ICJR, RC dan EJA di 2016 di PN Surabaya, dari seluruh pasal dakwaan yang digunakan dalam sample penelitian, baik dalam dakwaan pertama/primer/tunggal atau dakwaan kedua/subsidair, penggunaan Pasal 111/112 menempati urutan pertama dengan 48%. Urutan ke-dua ditempati pasal 127 dengan 33%, sedangkan pasal 114 berada diurutan ke-tiga dengan 18%. Sempintas, penggunaan pasal 111/112 tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasal 127, hanya berbeda 15%. Namun, dalam praktik dan tehnis persidangan, penggunaan pasal paling penting ketika dihubungkan dengan model dakwaan. Artinya, meskipun Jaksa ikut mendakwa terdakwa dengan Pasal 127, namun tetap mencantumkan pasal 111/112 atau 114, ini menunjukkan bahwa jaksa masih ingin menjerat terdakwa dengan penggunaan pasal 111/112 atau 114, yang secara unsur lebih mudah untuk dibuktikan. Hal tersebut terkonfirmasi dengan penggunaan pasal 111/112 yang maoyritas dicantumkan sebagai dakwaan primer/pertama, angkanya mencapai 63%, disusul pasal 114 yang dicantumkan di dakwaan pertama/primer sebanayak 37%. Tujuan menjerat terdakwa dengan pasal 111/112 atau 114 semakin nyata dengan temuan penggunaan pasal 127 di dakwaan primer/pertama yang berjumlah 0% atau nihil. Supriyadi W. Eddyono, et.al., Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan : Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya, Jakarta : ICJR dan Rumah Cemara, 2016, hlm. 44. Lihat http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/08/Studi-SEMA-dan-SEJA-Rehabilitasidalam-Praktek-Peradilan.pdf
[19] Miko S. Ginting, Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pengguna Narkotika: Dari Kriminalisasi Menuju Dekriminalisasi sebagaimana dimuat dalam Choky R. Ramadhan (ed), Anomali Kebijakan Narkotika, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), Hal. 35
[20] Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ps. 1 angka (15)
[21] Ibid, Penjelasan Ps. 54
[22] Ibid, Ps. 1 angka (13)
[23] Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ps. 127 ayat (3)
[24] Ibid, Ps. 103
[25] MaPPI FH U, op cit, Hal. 59
[26] Arif Rachman Iryawan dan Alfiana Qisthi, Perawatan dan Rehabilitasi Narkotika sebagaimana dimuat dalam Choky R. Ramadhan (ed), op cit, Hal. 26-27